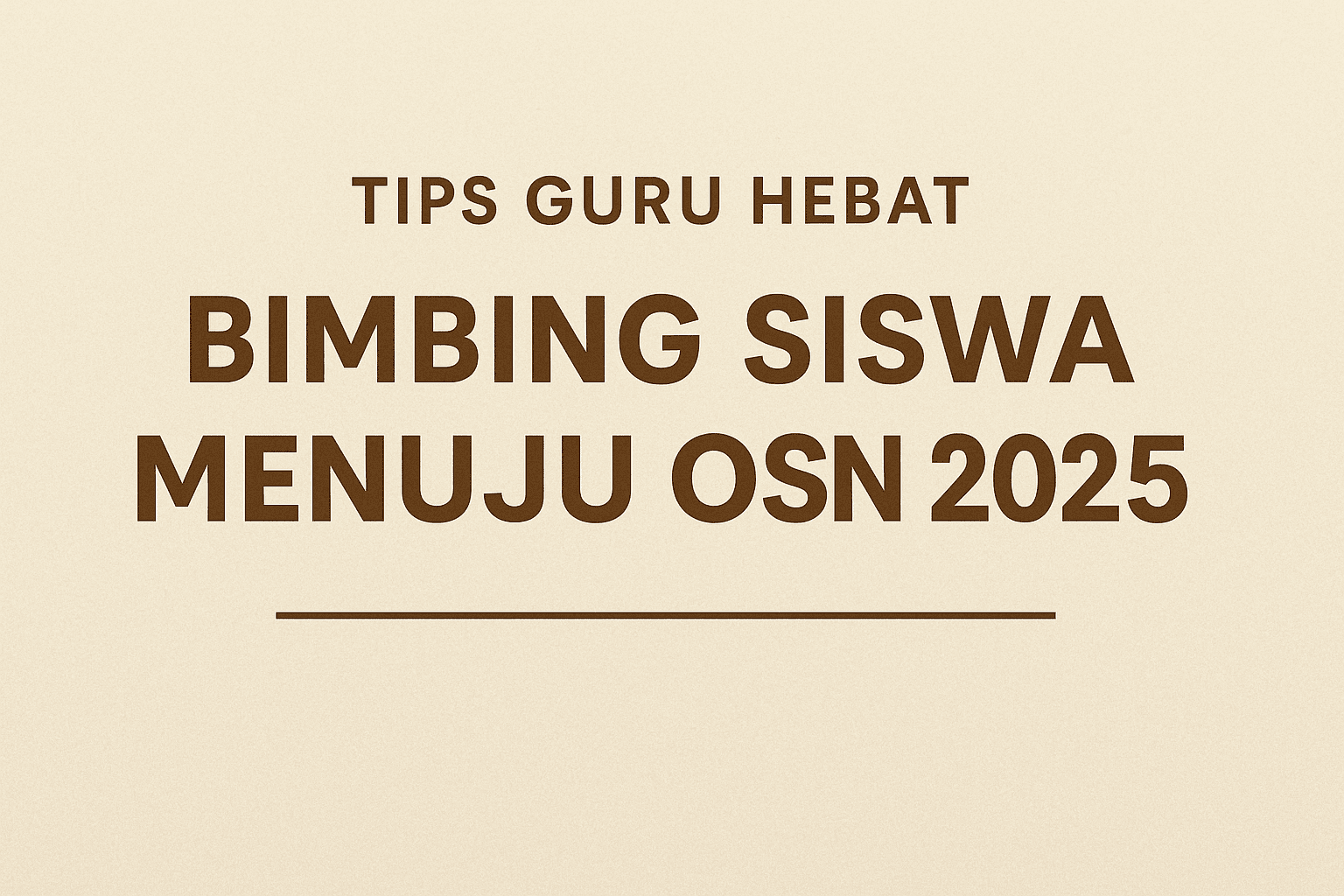Bayangkan sebuah taman luas yang dipenuhi bunga berwarna-warni. Ada yang tumbuh tinggi menjulang, ada yang mekar mungil namun wangi semerbak, ada pula yang sederhana tapi kuat bertahan di segala musim. Begitulah anak-anak kita—masing-masing membawa benih potensi yang unik. Tugas pendidikan sejatinya bukan menyeragamkan, melainkan merawat agar setiap bunga bisa tumbuh sesuai naluri bawaannya, sambil tetap berada dalam jalur yang terarah.
Namun, di ruang-ruang kelas hari ini, guru sering berdiri di antara dua arus besar. Di satu sisi, ada kurikulum formal yang menuntut administrasi rapi, target angka, dan capaian indikator. Di sisi lain, ada potensi alami anak—rasa ingin tahu, imajinasi, bakat unik, dan cara belajar khas yang tak selalu sejalan dengan buku teks.
Banyak guru yang hatinya rindu mendidik sesuai potensi anak. Namun realitas sering tak memberi cukup ruang. Lembar-lembar administrasi harus selesai, laporan harus masuk, nilai harus terisi. Tak jarang, energi habis untuk urusan kertas, sementara senyum dan pertanyaan polos anak-anak terlewat begitu saja.
Padahal kita tahu bersama: pendidikan sejati lahir dari perjumpaan jiwa. Anak belajar bukan hanya dari materi, melainkan dari pengalaman, rasa ingin tahu, dan hubungan yang hangat dengan gurunya. Potensi anak tumbuh ketika mereka merasa didengar, dihargai, dan diberi kesempatan menemukan caranya sendiri dalam belajar.
Setiap anak adalah unik. Ada yang cepat memahami angka, ada yang lebih peka pada seni, ada yang tangkas memimpin, ada pula yang punya empati luar biasa. Keragaman potensi itu ibarat mozaik, yang bila diberi ruang akan melahirkan keindahan luar biasa. Tugas pendidikan sejatinya adalah mengenali warna itu, lalu menuntunnya agar bersinar.
Apakah itu berarti kurikulum formal harus ditinggalkan? Tentu tidak. Administrasi dan standar tetap penting sebagai rambu, agar pendidikan punya arah. Namun, jangan sampai rambu itu berubah menjadi jeruji yang mematikan kreativitas. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan: bagaimana guru bisa memenuhi tuntutan formal, sekaligus tetap setia pada potensi murid.
Guru pun perlu dukungan nyata: sistem yang lebih manusiawi, kepala sekolah yang memahami, dan komunitas yang saling menguatkan. Karena pada akhirnya, guru yang merdeka batinnya, akan melahirkan murid yang merdeka pula jiwanya.
Potensi adalah benih yang perlu disirami; kurikulum adalah pagar yang menuntun jalannya — bila pagar rapat namun tanahnya subur, benih akan tumbuh, bersemi, dan memberi buah bagi dunia.
Bogor, 16 September 2025
Diana Bakti Siregar, S.Si